Jika Bahasa Melayu ditempatkan sebagai bahasa daerah, sangat mungkin para pakar bahasa (Indonesia) dan Pusat Bahasa, akan menghadapi tembok besar kegagalan. Bukankah salah satu syarat sebuah bahasa menjadi bahasa resmi PBB ditentukan oleh klaim bahwa bahasa itu telah menjadi bahasa negara, bukan bahasa daerah. Jika yang diusulkan Bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara, kendalanya sama saja, lantaran ia bukan sebagai bahasa negara. Jadi, yang diusulkan sebagai bahasa resmi PBB hendaklah bahasa negara, dan itu tidak lain adalah bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan beberapa negara ASEAN lainnya akan mendukung usulan itu?
Untuk melihat sejauh mana kemungkinan bahasa Indonesia dapat diterima sebagai bahasa resmi PBB, berikut ini akan dipaparkan argumen yang melandasinya, baik dilihat dari aspek kesejarahan, linguistik, maupun luas penyebarannya. Dalam konteks itulah, perlu kiranya kita menengok ke belakang pada sejarah perkembangan bahasa Indonesia.
Salah satu hasil Kongres Bahasa Indonesia II, di Medan tahun 1954, adalah disepakatinya pembentukan suatu badan yang khusus menyusun peraturan ejaan bahasa Indonesia. Alasannya, bahwa Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik yang ditetapkan tahun 1947, perlu disederhanakan dan disempurnakan lagi. Badan tersebut baru terbentuk tahun 1956. Setahun kemudian, berhasil dirumuskan patokan-patokan baru Ejaan Bahasa Indonesia yang terkenal dengan nama Ejaan Pembaharuan.
Belum sempat ejaan ini diresmikan, Persekutuan Tanah Melayu, yakni Malaysia dan sekitarnya, mengadakan kerja sama dengan Indonesia guna membentuk penyeragaman sistem ejaan kedua negara. Hasilnya adalah konsep Ejaan Melayu-Indonesia. Lalu terkenal dengan nama Ejaan Melindo (Melayu-Indonesia). Konsep ini pun, belum sempat diresmikan, lantaran kedua belah pihak terlibat konfrontasi.
Memasuki zaman Orde Baru, baik Indonesia maupun Malaysia menyadari bahwa sesungguhnya perselisihan antar-bangsa, terutama antar-negara bertetangga, tidaklah mendatangkan manfaat. Lalu, hubungan kedua negara pun dijalin kembali. Sebagai realisasi bentuk persahabatan itu, Ejaan Melindo yang pernah disepakati, dihidupkan kembali. Lahirlah Ejaan Baru tahun 1966.
Entah bagaimana pasalnya, ejaan yang terakhir ini pun tidak sempat diresmikan. Sementara itu, perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat, menuntut perlunya penyempurnaan ejaan dengan segera. Maka atas dasar berbagai pertimbangan, antara lain, perlunya penyesuaian ejaan Bahasa Indonesia dengan perkembangannya, ketertiban cara penulisan, usaha pembakuan Bahasa Indonesia secara menyeluruh, serta usaha pengembangannya, keluarlah Surat Keputusan Presiden Soeharto No 57 tentang peresmian berlakunya “Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan”.
Keputusan tersebut, tentulah tidak hanya atas pertimbangan segi kebahasaan semata-mata, melainkan juga ada sejumlah faktor lain yang tak dapat diabaikan. Dalam hubungannya dengan masalah itulah, kita akan melihat betapa tepat dan pentingnya pembakuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang sedang dalam proses pertumbuhannya. Lebih jauh lagi sebagai upaya untuk menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia.
Faktor Kesejarahan
Dalam perjalanan bahasa Indonesia sampai sekarang, yakni sejak dicetuskan pertama kali dalam butiran Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, pedoman ejaan Bahasa Indonesia secara resmi baru dua kali mengalami perubahan. Pertama, melalui Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Mr Soewandi, tanggal 19 Maret 1947, yang disusul dengan Surat Keputusan No 345/Bhg A, 15 April 1947. Kedua, Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 7/U/1972, Mashuri, yang kemudian diresmikan pemakaiannya melalui Surat Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972.
Sebelum Ejaan Soewandi, pedoman ejaan waktu itu masih menggunakan ejaan van Ophuijsen. Ejaan ini bersumber dari buku yang berjudul Kitab Logat Melajoe hasil penyusunan Charles Adriaan van Ophuijsen dibantu oleh Engkoe Nawawi Gelar Soetan Ma’moen dan Moehamad Ta’ib Soetan Ibrahim. Konsepnya sendiri sebenarnya dimulai tahun 1896, setahun sebelum AA Fokker mengusulkan penyeragaman ejaan Bahasa Melayu dengan huruf Latin. Namun baru diundangkan secara resmi oleh pemerintah Belanda tahun 1901.
Mengingat latar belakang diberlakukannya Ejaan van Ophuijsen, tindakan tersebut cukup punya arti penting bagi perjalanan Bahasa Melayu selanjutnya. Waktu itu, pengaruh Islam di wilayah Nusantara yang amat kuat, menyangkut juga soal bahasa. Masyarakat di Semenanjung Melayu dan sekitarnya, sudah terbiasa menggunakan huruf Arab-Melayu (huruf Jawi atau Pegon—bahasa Melayu dengan huruf Arab). Begitu juga di Pulau Jawa, bahasa daerah setempat banyak juga yang memakai huruf Pegon.
Di samping itu, jauh sebelum bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca bagi penduduk di kepualauan ini. Bahkan perhubungan dengan para pedagang asing seperti India, Arab, Cina, Portugis, dan Persia, juga menggunakan Bahasa Melayu. Dengan sendirinya, di beberapa daerah muncul dialek-dialek Melayu. Kosakata, ejaan, maupun struktur bahasa Melayu, jadi beragam.
Sungguhpun demikian, dialek Melayu Riau yang biasa digunakan oleh para sultan di kepulauan itu, tetap dianggap sebagai Bahasa Melayu Tinggi. Dengan kata lain, Bahasa Melayu yang dianggap standar dan baku waktu itu adalah Bahasa Melayu dialek Riau. Dialek itulah yang kemudian dijadikan model bagi van Ophuijsen dan dua rekannya untuk menyusun pedoman ejaan Bahasa Melayu.
Maka sejak tahun 1901, perkembangan Bahasa Melayu harus berpatokan pada pedoman Ejaan van Ophuijsen, yang pada hakikatnya berlandaskan pada Bahasa Melayu dialek Riau. Semua kosakata yang berasal dari bahasa asing —Cina, Arab, India, Inggris, Portugis, dan Belanda— serta yang berasal dari daerah-daerah di kawasan Nusantara, harus disesuaikan dengan ejaan Bahasa Melayu.
Perkembangan yang amat menonjol ditandai dengan berdirinya Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur (Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat), 14 September 1908, kurang dari empat bulan setelah lahir Boedi Oetomo, 20 Mei 1908. Buku-buku yang diterbitkan komisi ini diseleksi secara ketat. Tidak hanya isinya yang harus sejalan dengan garis politik kolonial Belanda, tetapi juga harus menggunakan Bahasa Melayu tinggi sesuai dengan Ejaan van Ophuijsen.
Pada tahun 1917, komisi ini berganti nama menjadi Kantor Voor de Volkslectuur (Balai Pustaka). Penggantian nama ini, sama sekali tidak mengubah kebijaksanaan sebelumnya. Kaidah-kaidah kebahasaan tetap berpedoman pada Ejaan van Ophuijsen. Di balik itu, para pemuda terpelajar kita makin merasakan pentingnya mempunyai bahasa sendiri. Emosi kebangsaan mereka makin menggelora. Sampai puncaknya, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah membulat tekadnya, “Bertanah airyang satu —Indonesia, berbangsa yang satu— Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan: bahasa Indonesia.”
Untuk melihat sejauh mana kemungkinan bahasa Indonesia dapat diterima sebagai bahasa resmi PBB, berikut ini akan dipaparkan argumen yang melandasinya, baik dilihat dari aspek kesejarahan, linguistik, maupun luas penyebarannya. Dalam konteks itulah, perlu kiranya kita menengok ke belakang pada sejarah perkembangan bahasa Indonesia.
Salah satu hasil Kongres Bahasa Indonesia II, di Medan tahun 1954, adalah disepakatinya pembentukan suatu badan yang khusus menyusun peraturan ejaan bahasa Indonesia. Alasannya, bahwa Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik yang ditetapkan tahun 1947, perlu disederhanakan dan disempurnakan lagi. Badan tersebut baru terbentuk tahun 1956. Setahun kemudian, berhasil dirumuskan patokan-patokan baru Ejaan Bahasa Indonesia yang terkenal dengan nama Ejaan Pembaharuan.
Belum sempat ejaan ini diresmikan, Persekutuan Tanah Melayu, yakni Malaysia dan sekitarnya, mengadakan kerja sama dengan Indonesia guna membentuk penyeragaman sistem ejaan kedua negara. Hasilnya adalah konsep Ejaan Melayu-Indonesia. Lalu terkenal dengan nama Ejaan Melindo (Melayu-Indonesia). Konsep ini pun, belum sempat diresmikan, lantaran kedua belah pihak terlibat konfrontasi.
Memasuki zaman Orde Baru, baik Indonesia maupun Malaysia menyadari bahwa sesungguhnya perselisihan antar-bangsa, terutama antar-negara bertetangga, tidaklah mendatangkan manfaat. Lalu, hubungan kedua negara pun dijalin kembali. Sebagai realisasi bentuk persahabatan itu, Ejaan Melindo yang pernah disepakati, dihidupkan kembali. Lahirlah Ejaan Baru tahun 1966.
Entah bagaimana pasalnya, ejaan yang terakhir ini pun tidak sempat diresmikan. Sementara itu, perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat, menuntut perlunya penyempurnaan ejaan dengan segera. Maka atas dasar berbagai pertimbangan, antara lain, perlunya penyesuaian ejaan Bahasa Indonesia dengan perkembangannya, ketertiban cara penulisan, usaha pembakuan Bahasa Indonesia secara menyeluruh, serta usaha pengembangannya, keluarlah Surat Keputusan Presiden Soeharto No 57 tentang peresmian berlakunya “Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan”.
Keputusan tersebut, tentulah tidak hanya atas pertimbangan segi kebahasaan semata-mata, melainkan juga ada sejumlah faktor lain yang tak dapat diabaikan. Dalam hubungannya dengan masalah itulah, kita akan melihat betapa tepat dan pentingnya pembakuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang sedang dalam proses pertumbuhannya. Lebih jauh lagi sebagai upaya untuk menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia.
Faktor Kesejarahan
Dalam perjalanan bahasa Indonesia sampai sekarang, yakni sejak dicetuskan pertama kali dalam butiran Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, pedoman ejaan Bahasa Indonesia secara resmi baru dua kali mengalami perubahan. Pertama, melalui Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Mr Soewandi, tanggal 19 Maret 1947, yang disusul dengan Surat Keputusan No 345/Bhg A, 15 April 1947. Kedua, Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 7/U/1972, Mashuri, yang kemudian diresmikan pemakaiannya melalui Surat Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972.
Sebelum Ejaan Soewandi, pedoman ejaan waktu itu masih menggunakan ejaan van Ophuijsen. Ejaan ini bersumber dari buku yang berjudul Kitab Logat Melajoe hasil penyusunan Charles Adriaan van Ophuijsen dibantu oleh Engkoe Nawawi Gelar Soetan Ma’moen dan Moehamad Ta’ib Soetan Ibrahim. Konsepnya sendiri sebenarnya dimulai tahun 1896, setahun sebelum AA Fokker mengusulkan penyeragaman ejaan Bahasa Melayu dengan huruf Latin. Namun baru diundangkan secara resmi oleh pemerintah Belanda tahun 1901.
Mengingat latar belakang diberlakukannya Ejaan van Ophuijsen, tindakan tersebut cukup punya arti penting bagi perjalanan Bahasa Melayu selanjutnya. Waktu itu, pengaruh Islam di wilayah Nusantara yang amat kuat, menyangkut juga soal bahasa. Masyarakat di Semenanjung Melayu dan sekitarnya, sudah terbiasa menggunakan huruf Arab-Melayu (huruf Jawi atau Pegon—bahasa Melayu dengan huruf Arab). Begitu juga di Pulau Jawa, bahasa daerah setempat banyak juga yang memakai huruf Pegon.
Di samping itu, jauh sebelum bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca bagi penduduk di kepualauan ini. Bahkan perhubungan dengan para pedagang asing seperti India, Arab, Cina, Portugis, dan Persia, juga menggunakan Bahasa Melayu. Dengan sendirinya, di beberapa daerah muncul dialek-dialek Melayu. Kosakata, ejaan, maupun struktur bahasa Melayu, jadi beragam.
Sungguhpun demikian, dialek Melayu Riau yang biasa digunakan oleh para sultan di kepulauan itu, tetap dianggap sebagai Bahasa Melayu Tinggi. Dengan kata lain, Bahasa Melayu yang dianggap standar dan baku waktu itu adalah Bahasa Melayu dialek Riau. Dialek itulah yang kemudian dijadikan model bagi van Ophuijsen dan dua rekannya untuk menyusun pedoman ejaan Bahasa Melayu.
Maka sejak tahun 1901, perkembangan Bahasa Melayu harus berpatokan pada pedoman Ejaan van Ophuijsen, yang pada hakikatnya berlandaskan pada Bahasa Melayu dialek Riau. Semua kosakata yang berasal dari bahasa asing —Cina, Arab, India, Inggris, Portugis, dan Belanda— serta yang berasal dari daerah-daerah di kawasan Nusantara, harus disesuaikan dengan ejaan Bahasa Melayu.
Perkembangan yang amat menonjol ditandai dengan berdirinya Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur (Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat), 14 September 1908, kurang dari empat bulan setelah lahir Boedi Oetomo, 20 Mei 1908. Buku-buku yang diterbitkan komisi ini diseleksi secara ketat. Tidak hanya isinya yang harus sejalan dengan garis politik kolonial Belanda, tetapi juga harus menggunakan Bahasa Melayu tinggi sesuai dengan Ejaan van Ophuijsen.
Pada tahun 1917, komisi ini berganti nama menjadi Kantor Voor de Volkslectuur (Balai Pustaka). Penggantian nama ini, sama sekali tidak mengubah kebijaksanaan sebelumnya. Kaidah-kaidah kebahasaan tetap berpedoman pada Ejaan van Ophuijsen. Di balik itu, para pemuda terpelajar kita makin merasakan pentingnya mempunyai bahasa sendiri. Emosi kebangsaan mereka makin menggelora. Sampai puncaknya, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah membulat tekadnya, “Bertanah airyang satu —Indonesia, berbangsa yang satu— Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan: bahasa Indonesia.”
Ikrar para pemuda itu, pada awalnya bersifat politis, namun sesungguhnya dalam perkembangannya benar-benar telah mampu meleburkan persoalan suku, adat, ras, dan agama. Kepentingan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari kepentingan lainnya. Dengan demikian, tekad untuk mengusir penjajah, serta hasrat untuk membentuk negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat, nyata sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Melihat Kelemahan
Dalam persoalan bahasa, para pemuda terpelajar kita mulai melihat adanya beberapa kelemahan yang terdapat dalam Ejaan van Ophuijsen. Khususnya ketidakcocokan konsep gramatika Belanda dan Arab yang diterapkan dalam Bahasa Melayu. Fonem-fonem asing seperti ain, hamzah, ch, sj, oe, dl, dan ts, seringkali menimbulkan cara penulisan dan pembacaan yang keliru. Lantaran itulah, dalam Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 25—28 Juni 1938, diputuskan perlunya ejaan baru, di samping gagasan untuk menyempurnakan dan menyederhanakan Ejaan van Ophuijsen.
Ternyata, tindak lanjutnya baru dilakukan dua tahun setelah Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara yang tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Mr Soewandi, 19 Maret dan 15 April 1947, mencanangkan penggantian Ejaan van Ophuijsen dengan Ejaan Republik.
Beberapa perubahan yang dilakukan, antara lain, digantinya fonem oe menjadi u, bunyi vokal e (E) dan e (e) diwakili oleh satu fonem e serta ucapan kata-kata asing atau pinjaman yang disesuaikan dengan cara pengucapan bahasa Indonesia. Namun, bentuk kata yang diulang masih dibolehkan memakai angka dua (2). Hal ini tentu saja dapat mengacaukan dengan kata ulang atau reduplikasi, seperti kupu-kupu, paru-paru, biri-biri, dan banyak lagi reduplikasi yang sebenarnya bukan merupakan kata yang diulang.
Sejumlah kelemahan yang terkandung dalam Ejaan Soewandi, dikecam cukup pedas oleh Prof Dr Prijono. Menurutnya, Ejaan Soewandi tidak lebih dari “pindah tulis” dan bentuk lain dari Ejaan van Ophuijsen. Lalu dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, 23 Oktober—2 November 1954, mulailah Ejaan Soewandi “ditinjau” kembali.
Setelah tersusun konsep Ejaan Pembaharuan atau yang dikenal juga dengan nama Ejaan Prijono—Katoppo, Persekutuan Tanah Melayu mengadakan kerja sama dengan Indonesia guna menyusun pedoman ejaan bagi kedua negara itu. Namun batal diresmikan karena terjadi konfrontasi. Baru kemudian dihidupkan kembali lewat pertemuan di Kuala Lumpur 21—23 Juni 1967, dengan nama Ejaan Baru Bahasa Indonesia untuk Indonesia dan Ejaan Baru Bahasa Melayu untuk Malaysia.
Sebenarnya, konsep ejaan ini bertumpu pada konsep hasil penyusunan Panitia Crash Program Ejaan Bahasa Indonesia LBK, Agustus 1966. Panitia yang diketuai oleh Anton M Moeliono ini, mendasari konsepnya atas konsep Ejaan Pembaharuan tahun 1957, dan Ejaan Melindo tahun 1959, serta berpegang pada prinsip “satu fonem, satu tanda”.
Hambatan utama terlaksananya hasil rumusan panitia tersebut, sebenarnya lebih menyangkut soal pembiayaan daripada soal kebahasaan. Maka atas berbagai pertimbangan, rumusan itu mengalami beberapa perubahan lagi. Sampai kemudian, keluarlah keputusan yang memberlakukan Ejaan Yang Disempurnakan, 17 Agustus 1972.
Menuju Bahasa Dunia
Pada masa awal diberlakukannya EYD (Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan), reaksi timbul dari berbagai kalangan. Yang tidak setuju, umumnya melihat dari segi pembiayaan semata-mata. Sedangkan yang setuju, melihatnya jauh ke depan. Sesungguhnya, Keputusan Presiden No 57 itu ibarat langkah yang tidak hanya hendak mengokohkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, melainkan juga upaya mendudukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN dan bahasa dunia.
Melihat Kelemahan
Dalam persoalan bahasa, para pemuda terpelajar kita mulai melihat adanya beberapa kelemahan yang terdapat dalam Ejaan van Ophuijsen. Khususnya ketidakcocokan konsep gramatika Belanda dan Arab yang diterapkan dalam Bahasa Melayu. Fonem-fonem asing seperti ain, hamzah, ch, sj, oe, dl, dan ts, seringkali menimbulkan cara penulisan dan pembacaan yang keliru. Lantaran itulah, dalam Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 25—28 Juni 1938, diputuskan perlunya ejaan baru, di samping gagasan untuk menyempurnakan dan menyederhanakan Ejaan van Ophuijsen.
Ternyata, tindak lanjutnya baru dilakukan dua tahun setelah Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara yang tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Mr Soewandi, 19 Maret dan 15 April 1947, mencanangkan penggantian Ejaan van Ophuijsen dengan Ejaan Republik.
Beberapa perubahan yang dilakukan, antara lain, digantinya fonem oe menjadi u, bunyi vokal e (E) dan e (e) diwakili oleh satu fonem e serta ucapan kata-kata asing atau pinjaman yang disesuaikan dengan cara pengucapan bahasa Indonesia. Namun, bentuk kata yang diulang masih dibolehkan memakai angka dua (2). Hal ini tentu saja dapat mengacaukan dengan kata ulang atau reduplikasi, seperti kupu-kupu, paru-paru, biri-biri, dan banyak lagi reduplikasi yang sebenarnya bukan merupakan kata yang diulang.
Sejumlah kelemahan yang terkandung dalam Ejaan Soewandi, dikecam cukup pedas oleh Prof Dr Prijono. Menurutnya, Ejaan Soewandi tidak lebih dari “pindah tulis” dan bentuk lain dari Ejaan van Ophuijsen. Lalu dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, 23 Oktober—2 November 1954, mulailah Ejaan Soewandi “ditinjau” kembali.
Setelah tersusun konsep Ejaan Pembaharuan atau yang dikenal juga dengan nama Ejaan Prijono—Katoppo, Persekutuan Tanah Melayu mengadakan kerja sama dengan Indonesia guna menyusun pedoman ejaan bagi kedua negara itu. Namun batal diresmikan karena terjadi konfrontasi. Baru kemudian dihidupkan kembali lewat pertemuan di Kuala Lumpur 21—23 Juni 1967, dengan nama Ejaan Baru Bahasa Indonesia untuk Indonesia dan Ejaan Baru Bahasa Melayu untuk Malaysia.
Sebenarnya, konsep ejaan ini bertumpu pada konsep hasil penyusunan Panitia Crash Program Ejaan Bahasa Indonesia LBK, Agustus 1966. Panitia yang diketuai oleh Anton M Moeliono ini, mendasari konsepnya atas konsep Ejaan Pembaharuan tahun 1957, dan Ejaan Melindo tahun 1959, serta berpegang pada prinsip “satu fonem, satu tanda”.
Hambatan utama terlaksananya hasil rumusan panitia tersebut, sebenarnya lebih menyangkut soal pembiayaan daripada soal kebahasaan. Maka atas berbagai pertimbangan, rumusan itu mengalami beberapa perubahan lagi. Sampai kemudian, keluarlah keputusan yang memberlakukan Ejaan Yang Disempurnakan, 17 Agustus 1972.
Menuju Bahasa Dunia
Pada masa awal diberlakukannya EYD (Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan), reaksi timbul dari berbagai kalangan. Yang tidak setuju, umumnya melihat dari segi pembiayaan semata-mata. Sedangkan yang setuju, melihatnya jauh ke depan. Sesungguhnya, Keputusan Presiden No 57 itu ibarat langkah yang tidak hanya hendak mengokohkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, melainkan juga upaya mendudukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN dan bahasa dunia.
Dalam lingkup ASEAN, tampaknya Filipina dan Muangthai saja yang mungkin masih merasakan beberapa hambatan. Sungguhpun demikian, berdasarkan unsur kekerabatan, korespondensi fonemis, faktor geografis, struktur gramatika, maupun unsur kebahasaan lainnya, bahasa Tagalog di Filipina dan bahasa Siam di Muangthai, mempunyai hubungan yang erat dengan Bahasa Melayu yang merupakan asal dan dasar Bahasa Indonesia. Begitu juga dengan Bahasa Cham di Kamboja.
Apabila kita membandingkan sejumlah kosa kata yang terdapat di negara-negara tersebut —seperti yang dilakukan Gorys Keraf dalam bukunya, Linguistik Historis Komparatif— kita akan mendapatkan bukti kuat, bahwa bahasa-bahasa di kawasan Asia Tenggara (rumpun bahasa Austronesia) sebenarnya masih satu keluarga bahasa yang sama. Kita tak perlu heran, jika orang Filipina berkata ku:lang (kurang), ilung (hidung), dan bu’guk (buruk). Pendeknya, bahasa Tagalog dengan Bahasa Melayu umumnya mempunyai bentuk dan bunyi yang mirip, bahkan sama.
Bukti lain dapat kita lihat dari hasil penelitian Dr H Kern tahun 1889. Ia membandingkan sejumlah kata dari 100 bahasa yang tersebar dari Malagasi sampai Amerika Selatan. Kesimpulannya, mustahil jika kesamaan bunyi dan bentuk dari nama-nama tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terdapat di kawasannya, terjadi secara kebetulan. Artinya, dapat dilacak lebih jauh adanya hubungan kerabat dari satu nenek moyang atau protobahasa yang sama.
Jadi jelas, Bahasa Melayu bagi negara-negara ASEAN, sesungguhnya dapat pula mempererat hubungan antar-negara bertetangga ini. Malaysia, Singapura, dan Brunei, bahkan juga di Muangthai (khasnya Patani) dan Filipina (khasnya Mindanau), menyadari hal itu. Malaysia menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Demikian juga Brunei Darussalam sejak tahun 1959 —sebagaimana yang dinyatakan Pangeran Badaruddin— “bahwa Bahasa Melayu adalah bahasa resmi dan mesti digunakan di dalam segala bidang.”
Bagi Indonesia, persoalan tentu tidak semata-mata menjadikan bahasa Melayu (baca: Indonesia) sebagai bahasa resmi ASEAN, tetapi juga sebagai bahasa resmi dunia, seperti juga bahasa Inggris atau Perancis. Dan syarat-syarat untuk itu, memang sudah dimiliki Bahasa Indonesia. Antara lain, Bahasa Indonesia merupakan lingua franca bagi lebih dari 136 juta penduduk, bentuk dan strukturnya mudah dipelajari dan sederhana, bentuk tulisan dan ujaran tidak mengandung banyak perbedaan, menyerap secara bebas unsur dan istilah bahasa asing, mampu digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, serta merupakan mata ajaran wajib di semua tingkatan sekolah.
Lebih dari itu, bahasa Indonesia juga sudah diajarkan di banyak perguruan tinggi negara-negara sahabat. Tokyo, Seoul, Beijing, Melbourne, Canberra, Cornel, Yale, Mokow, Paris, Praha, Leiden, Warsawa, Berlin, Mesir, dan banyak lagi universitas di luar negeri yang membuka jurusan tersendiri tentang bahasa dan kesusastraan Indonesia. Paling sedikit, memberikan mata ajaran Bahasa Indonesia. Ini merupakan satu indikasi, betapa Bahasa Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi bahasa resmi internasional.
Melihat kenyataan tersebut, tidaklah sepatutnya jika masih ada suara sumbang yang meremehkan peran Bahasa Indonesia. Tidak patut pula jika kita tidak bangga pada bahasa sendiri. Dalam menyikapi perkembangan zaman dan arus globalisasi, peran bahasa Indonesia tentu berlainan dengan waktu pertama kali dicanangkan dalam ikrar Sumpah Pemuda. Jika dulu mampu berperan sebagai alat persatuan dan kesatuan bangsa, maka kini, mampukah ia mengangkat citra keagungan bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, gagasan untuk menempatkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia atau bahasa resmi PBB sesungguhnya lebih terterima dibandingkan dengan Bahasa Melayu. Semoga saja harapan ini menjadi kenyataan.
Apabila kita membandingkan sejumlah kosa kata yang terdapat di negara-negara tersebut —seperti yang dilakukan Gorys Keraf dalam bukunya, Linguistik Historis Komparatif— kita akan mendapatkan bukti kuat, bahwa bahasa-bahasa di kawasan Asia Tenggara (rumpun bahasa Austronesia) sebenarnya masih satu keluarga bahasa yang sama. Kita tak perlu heran, jika orang Filipina berkata ku:lang (kurang), ilung (hidung), dan bu’guk (buruk). Pendeknya, bahasa Tagalog dengan Bahasa Melayu umumnya mempunyai bentuk dan bunyi yang mirip, bahkan sama.
Bukti lain dapat kita lihat dari hasil penelitian Dr H Kern tahun 1889. Ia membandingkan sejumlah kata dari 100 bahasa yang tersebar dari Malagasi sampai Amerika Selatan. Kesimpulannya, mustahil jika kesamaan bunyi dan bentuk dari nama-nama tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terdapat di kawasannya, terjadi secara kebetulan. Artinya, dapat dilacak lebih jauh adanya hubungan kerabat dari satu nenek moyang atau protobahasa yang sama.
Jadi jelas, Bahasa Melayu bagi negara-negara ASEAN, sesungguhnya dapat pula mempererat hubungan antar-negara bertetangga ini. Malaysia, Singapura, dan Brunei, bahkan juga di Muangthai (khasnya Patani) dan Filipina (khasnya Mindanau), menyadari hal itu. Malaysia menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Demikian juga Brunei Darussalam sejak tahun 1959 —sebagaimana yang dinyatakan Pangeran Badaruddin— “bahwa Bahasa Melayu adalah bahasa resmi dan mesti digunakan di dalam segala bidang.”
Bagi Indonesia, persoalan tentu tidak semata-mata menjadikan bahasa Melayu (baca: Indonesia) sebagai bahasa resmi ASEAN, tetapi juga sebagai bahasa resmi dunia, seperti juga bahasa Inggris atau Perancis. Dan syarat-syarat untuk itu, memang sudah dimiliki Bahasa Indonesia. Antara lain, Bahasa Indonesia merupakan lingua franca bagi lebih dari 136 juta penduduk, bentuk dan strukturnya mudah dipelajari dan sederhana, bentuk tulisan dan ujaran tidak mengandung banyak perbedaan, menyerap secara bebas unsur dan istilah bahasa asing, mampu digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, serta merupakan mata ajaran wajib di semua tingkatan sekolah.
Lebih dari itu, bahasa Indonesia juga sudah diajarkan di banyak perguruan tinggi negara-negara sahabat. Tokyo, Seoul, Beijing, Melbourne, Canberra, Cornel, Yale, Mokow, Paris, Praha, Leiden, Warsawa, Berlin, Mesir, dan banyak lagi universitas di luar negeri yang membuka jurusan tersendiri tentang bahasa dan kesusastraan Indonesia. Paling sedikit, memberikan mata ajaran Bahasa Indonesia. Ini merupakan satu indikasi, betapa Bahasa Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi bahasa resmi internasional.
Melihat kenyataan tersebut, tidaklah sepatutnya jika masih ada suara sumbang yang meremehkan peran Bahasa Indonesia. Tidak patut pula jika kita tidak bangga pada bahasa sendiri. Dalam menyikapi perkembangan zaman dan arus globalisasi, peran bahasa Indonesia tentu berlainan dengan waktu pertama kali dicanangkan dalam ikrar Sumpah Pemuda. Jika dulu mampu berperan sebagai alat persatuan dan kesatuan bangsa, maka kini, mampukah ia mengangkat citra keagungan bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, gagasan untuk menempatkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia atau bahasa resmi PBB sesungguhnya lebih terterima dibandingkan dengan Bahasa Melayu. Semoga saja harapan ini menjadi kenyataan.
 Post
Post 








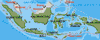
















4 komentar:
info yang bagus brow, oh ya, saya udah pasang link di blog saya, back linknnya yah, tnhx
ini menambah pengetahuan sy sbg pemula
Nice info...
Thx udh share...
czemu nie:)
Posting Komentar