Lihatlah. Tuminah duduk menekur. Sudah tiga hari ini perutnya mual-mual. Beberapa kali muntah. Lihat wajahnya! Pucat dan sesekali ia mengusap perutnya.
Tuminah, Tuminah, gadis desa yang lugu dan polos. Sungguh jelek nasibnya. Sebelas tahun usianya waktu bapaknya meninggal. Dan emaknya pun menyusul pula ke alam baqa dua tahun kemudian. Kanker ganas merenggut nyawanya. Tapi orang-orang menyebutnya kena santet. Maklum orang desa.
Tuminah perempuan lugu. Ia tinggalkan desa. Pergi ke kota jadi babu. Masih enam belas tahun umurnya saat itu. Tak ada pilihan lain. Adiknya masih kecil-kecil dan mesti ikut neneknya. Ia pun diasuh sang nenek. Lo, kenapa kini ia tinggalkan mereka?
Di desa susah cari kerja. Jadi buruh tani di sawah Pak Haji Munir tak cukup. Dia kepingin kedua adiknya bisa sekolah terus. Enggak seperti dirinya. Cuma tamat SD. Dan, kata orang di kota banyak uang. Gampang cari duit. Di mana-mana katanya ada duit.
Di kota banyak hiburan. Enggak kayak di desa. Cuma ada jatilan dan tayuban. Itu pun kalau ada yang mantenan atau sunatan. Di kota ada dangdut. Bisa lihat Elpi Sukesih.
Tuminah perempuan desa. Pergi ke kota jadi babu. Ia tinggalkan adik-adiknya. Ia tinggalkan Marjono, kekasihnya.
Sepi. Rumah gede dan gedongan siang itu sepi. Tuan dan Nyonya berangkat ke kantor. Non Sarah dan Non Kiki ke sekolah. Ah, kadang Tuminah takut kalau sepi begini. Takut kalau-kalau Tuan tiba-tiba pulang. Takut kalau-kalau.... Tuminah segera menepiskan bayangan buruk dan mengalihkannya pada bayangan kekasihnya.
Sedang apa Marjono sekarang? Sedang mencangkul di ladang? Atau lagi cari rumput untuk kambingnya? Oh, Kang Jon, aku kangen, bisik Tuminah dalam hati.
Tuminah gadis desa yang lugu. Ia tidak jelek. Hitam manis kulitnya. Sebahu panjang rambutnya. Oval bentuk wajahnya. Tinggi semampai tubuhnya. Ramping. Tapi jelek nasibnya.
Lihatlah. Tiba-tiba ia menangis sesunggukan. Bagaimana jika kang Jono tahu kalau aku... "Tet.. tet.. tet!" Aduh! Tuan datang. Kemana, ya, Pak Sarmin tadi. Oh, dia ngantarkan Non Sarah dan Non Kiki ke sekolah. Tuminah segera mengusap pipinya dengan punggung tangannya. Lalu bergegas lari untuk membukakan pintu pagar.
"Tolong bawakan tasku," perintah Tuan. "Aku terpaksa pulang. Lagi masuk angin. Tolong kerokin, ya, Tum?"
Aduh, gawat. Jurus yang kemarin-kemarin masih dipakai. Minta dikerokin lantas aku ditindihin.
Tuminah memang lagi apes. Ia tak mampu menolak seperti juga hari-hari kemarin. Mulanya juga seperti itu. Rumah lagi sepi. Tuan pulang siang. Pura-pura masuk angin. Minta dikerokin. Lalu sang Tuan merayu, membujuk, merangsang, dan terjadilah perzinaan itu. Tepatnya pemerkosaan.
Siang itu pun Tuminah mengeroki sang Tuan. Di kamar dulu-dulu juga. Yang ber-AC. Di atas kasur empuk... empuuuk sekali... namanya springbad. Tapi, ketika usai kerokan, Tuan merayu, Tuminah menangis dan dengan terus terang ia bilang: "Tuan, saya hamil."
"Hamil?" Tuan diam sejenak. "Tak usah khawatir. Aku punya kenalan dokter yang biasa praktik aborsi," lanjutnya santai.
"Obor... apa itu, Tuan?" Tuminah tak paham.
"Aborsi. Menggugurkan kandungan," jawab Tuan.
"Tidak Tuan. Saya takut." Tuminah tiba-tiba menggigil.
"Tidak perlu takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak sakit," hibur Tuan.
"Bukan itu, Tuan. Dosa, Tuan. Saya tak berani." Tuminah tambah tersedu-sedu.
"Pokoknya harus diaborsi. Kalau tak mau, kamu pulang saja."
Tuminah memang lagi nahas. Apes. Jelek nasibnya. Kalau sudah begini, apa kata orang? Tuminah hamil di luar nikah. Dihamili majikan. Jika ia pulang kampung, dalam keadaan bunting bayi haram, apa kata orang sekampung. Pasti semua orang akan mengejeknya. Tapi, kalau ia gugurkan kandungannya, ah... deretan dosanya tambah panjang. Ia sudah berkali-kali terpaksa melakukan pergumulan itu. Itu dosa. Lalu ... menggugurkan kandungan? Tidak! Tidak mungkin aku membunuh bayiku sendiri.
Tuminah memang gadis lugu. Polos hatinya. Ia tak tega menggugurkan kandungan yang berarti membunuh calon bayi. Ia takut. Takuuut sekali. Dan akhirnya ia putuskan: pulang.
Lihatlah, Tuminah menunduk tatkala hendak pamitan. Tas berisi beberapa lembar pakaian telah ia siapkan. Air matanya menetes. Sebenarnya ia sudah kerasan tinggal di rumah gede itu walau cuma jadi babu. Sesungguhnya Nyonya dan Tuan baik. Non Sarah dan Non Kiki pun sayang kepadanya. Tak pernah rewel. Nurut. Dan, mereka pun akrab dengan Tuminah. Tak pernah ia dimarahi. Tak pernah dibentak. Itu semua karena Tuminah anak yang baik. Pekerjaannya senantiasa beres. Perilakunya sopan, tutur katanya lembut, dan ia memang manis. Tapi, gairah Tuan yang membara itu tatkala menindihi tubuhnya di ranjang mewah di kasur empuk itu begitu menakutkan. Apalagi buah yang dihasilkan dari "pergaulan" terlarang itu, sungguh sebuah aib.
"Nyonya, maafkan saya," ucap Tuminah tersendat-sendat. "Saya mesti pulang."
"Lo, kenapa, Tum? Kamu tak betah tinggal di sini?" Sang Nyonya heran.
"Bukan karena itu, Nyonya." Tuminah agak tergagap.
"Lantas kenapa? Kami semua sayang kepadamu. Anak-anak juga begitu. Mereka akan kehilangan kamu, Tum. Apakah kami sering memarahimu? Atau gajimu terlalu kecil?" Nyonya membelai rambut Tuminah.
Tuminah menggeleng.
"Lalu kenapa?" Nyonya masih tampak heran.
Nyonya tak pernah mengerti. Bahkan tak memperhatikan perut Tuminah yang berisi janin hasil pergaulannya dengan Tuan, suaminya.
"Saya kangen nenek. Rindu kampung," dusta Tuminah sambil menunduk.
"Baiklah kalau begitu. Kami tak bisa memaksamu untuk tetap tinggal di sini. Tapi kalau kamu hendak kembali kemari suatu saat, pasti kami menerimamu dengan senang hati." Akhirnya Nyonya terpaksa merelakan.
Tuminah, Tuminah, perempuan desa yang lugu. Ke kota cuma jadi babu. Lantas dihamili majikan. Kini pulang kampung dengan membawa oleh-oleh: aib. Tapi itu lebih baik ketimbang membunuh bayi yang sudah empat bulan.
Marjono? Entahlah. Tuminah sudah sumpek. Bunuh diri? Tidak. Katanya bunuh diri itu dosa besar. Akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Lalu? Biarlah dan entahlah.
Tuminah yang malang. Nenek tak bakal bisa menerima anak jadah. Orang sedesa pun geger. Semua orang mencemooh anak yatim piatu itu. Dan, Marjono, kekasih tercinta itu....
"Tak kusangka, Tum. Aib menimpamu. Sungguh kejam," begitu komentar Marjono.
"Lantas bagaimana, Kang. Aku pasrah," ucap Tuminah sambil sesenggukan di pangkuan pemuda berkulit cokelat itu.
"Maafkan aku, Tum. Aku tak bisa menerimamu kembali," cetus Marjono terbata.
Bayi itu lahir juga pada akhirnya. Cakep dan montok. Tapi nenek tak bisa menerimanya. Bayi tak berdosa itu, kenapa dikatakan anak jadah, anak haram? Semua orang pun tetap tak bisa menerima kehadiran bayi itu. Katanya akan bikin sial. Tapi, Tuminah tak akan membuangnya di tempat sampah. Tak akan!
Tuminah sungguh polos hatinya. Perempuan desa ke kota jadi babu, pulang ke kampung membawa aib, kini kembali ke kota membawa bayi. Oleh-oleh buat sang Nyonya. Dan ia sendiri punya rencana lain. Ia telah memutuskan rencana itu.
Lihat! Tuminah berdiri di depan rumah gedongan di kawasan perumahan elite di Jakarta Selatan. Tangan kiri menjinjing tas. Tangan kanan memeluk bayi dalam seledang usang. Rumah itu tampak angkuh. Sepi. Ia menunggu pintu pagar terbuka. Ia menunggu sampai ada penghuni rumah itu melihatnya.
Benar. Nyonya tampak keluar pintu. Jantung Tuminah berdegup kencang. Adakah ia mau menerimaku kembali? Nyonya tampak ragu. Lalu ia mendekat. Menyaksikan dari dekat perempuan malang itu.
"Oh, Tuminah, akhirnya kamu kembali. Apa kataku. Anak-anak sering menanyakanmu, lo. Ayoh, masuk," ucap Nyonya senang sambil membuka pintu pagar.
Tuminah hanya mengangguk. Tetap berdiri mematung.
Nyonya tiba-tiba mengerutkan dahinya. Matanya tajam memandang wajah bayi dalam gendongan Tuminah.
"Tum, bayi siapa itu? Anakmu?" Nyonya tertegun.
Tuminah mengangguk.
"Cakep anakmu, Tum," puji Nyonya sambil mengelus kepala si bayi. Lalu menggendongnya. Tapi....
"Nyonya, maafkan saya, saya kemari hanya untuk menitipkan bayi ini," cetus Tuminah.
"Menitipkan....," Nyonya masih dilanda rasa heran.
Sekali lagi Tuminah mengangguk. "Saya nekat, Nyonya. Nekat jadi te-ka-we saja. Di Arab Saudi. Diajak Juminten dan Asih."
"Lo, maksudmu apa, Tum? Ini bayimu kamu titipkan di sini. Lantas kamu mau jadi TKW. La, bapaknya mana?"
"Ini anak Tuan. Saya... dulu diperkosa. Saya tak bisa menolak. Maafkan saya...."
Tuminah gadis desa. Ke kota jadi babu, pulang ke kampung bawa aib, kembali ke kota cuma menitipkan bayi, lantas kini mau jadi TKW. Tuminah memang lugu. Belum tahu dia. Di negeri ini atau di Arab Saudi atau di mana saja, "kecelakaan" itu akan terus terjadi, selama manusia tetap manusia, bukan malaikat. Tapi tekadnya sudah bulat, seraya berharap: semoga aib ini tidak terulang di Arab nanti. Nenek dan orang sedesa tak mau menerima anak jadah.
Tuminah, Tuminah, gadis desa yang lugu dan polos. Sungguh jelek nasibnya. Sebelas tahun usianya waktu bapaknya meninggal. Dan emaknya pun menyusul pula ke alam baqa dua tahun kemudian. Kanker ganas merenggut nyawanya. Tapi orang-orang menyebutnya kena santet. Maklum orang desa.
Tuminah perempuan lugu. Ia tinggalkan desa. Pergi ke kota jadi babu. Masih enam belas tahun umurnya saat itu. Tak ada pilihan lain. Adiknya masih kecil-kecil dan mesti ikut neneknya. Ia pun diasuh sang nenek. Lo, kenapa kini ia tinggalkan mereka?
Di desa susah cari kerja. Jadi buruh tani di sawah Pak Haji Munir tak cukup. Dia kepingin kedua adiknya bisa sekolah terus. Enggak seperti dirinya. Cuma tamat SD. Dan, kata orang di kota banyak uang. Gampang cari duit. Di mana-mana katanya ada duit.
Di kota banyak hiburan. Enggak kayak di desa. Cuma ada jatilan dan tayuban. Itu pun kalau ada yang mantenan atau sunatan. Di kota ada dangdut. Bisa lihat Elpi Sukesih.
Tuminah perempuan desa. Pergi ke kota jadi babu. Ia tinggalkan adik-adiknya. Ia tinggalkan Marjono, kekasihnya.
Sepi. Rumah gede dan gedongan siang itu sepi. Tuan dan Nyonya berangkat ke kantor. Non Sarah dan Non Kiki ke sekolah. Ah, kadang Tuminah takut kalau sepi begini. Takut kalau-kalau Tuan tiba-tiba pulang. Takut kalau-kalau.... Tuminah segera menepiskan bayangan buruk dan mengalihkannya pada bayangan kekasihnya.
Sedang apa Marjono sekarang? Sedang mencangkul di ladang? Atau lagi cari rumput untuk kambingnya? Oh, Kang Jon, aku kangen, bisik Tuminah dalam hati.
Tuminah gadis desa yang lugu. Ia tidak jelek. Hitam manis kulitnya. Sebahu panjang rambutnya. Oval bentuk wajahnya. Tinggi semampai tubuhnya. Ramping. Tapi jelek nasibnya.
Lihatlah. Tiba-tiba ia menangis sesunggukan. Bagaimana jika kang Jono tahu kalau aku... "Tet.. tet.. tet!" Aduh! Tuan datang. Kemana, ya, Pak Sarmin tadi. Oh, dia ngantarkan Non Sarah dan Non Kiki ke sekolah. Tuminah segera mengusap pipinya dengan punggung tangannya. Lalu bergegas lari untuk membukakan pintu pagar.
"Tolong bawakan tasku," perintah Tuan. "Aku terpaksa pulang. Lagi masuk angin. Tolong kerokin, ya, Tum?"
Aduh, gawat. Jurus yang kemarin-kemarin masih dipakai. Minta dikerokin lantas aku ditindihin.
Tuminah memang lagi apes. Ia tak mampu menolak seperti juga hari-hari kemarin. Mulanya juga seperti itu. Rumah lagi sepi. Tuan pulang siang. Pura-pura masuk angin. Minta dikerokin. Lalu sang Tuan merayu, membujuk, merangsang, dan terjadilah perzinaan itu. Tepatnya pemerkosaan.
Siang itu pun Tuminah mengeroki sang Tuan. Di kamar dulu-dulu juga. Yang ber-AC. Di atas kasur empuk... empuuuk sekali... namanya springbad. Tapi, ketika usai kerokan, Tuan merayu, Tuminah menangis dan dengan terus terang ia bilang: "Tuan, saya hamil."
"Hamil?" Tuan diam sejenak. "Tak usah khawatir. Aku punya kenalan dokter yang biasa praktik aborsi," lanjutnya santai.
"Obor... apa itu, Tuan?" Tuminah tak paham.
"Aborsi. Menggugurkan kandungan," jawab Tuan.
"Tidak Tuan. Saya takut." Tuminah tiba-tiba menggigil.
"Tidak perlu takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak sakit," hibur Tuan.
"Bukan itu, Tuan. Dosa, Tuan. Saya tak berani." Tuminah tambah tersedu-sedu.
"Pokoknya harus diaborsi. Kalau tak mau, kamu pulang saja."
Tuminah memang lagi nahas. Apes. Jelek nasibnya. Kalau sudah begini, apa kata orang? Tuminah hamil di luar nikah. Dihamili majikan. Jika ia pulang kampung, dalam keadaan bunting bayi haram, apa kata orang sekampung. Pasti semua orang akan mengejeknya. Tapi, kalau ia gugurkan kandungannya, ah... deretan dosanya tambah panjang. Ia sudah berkali-kali terpaksa melakukan pergumulan itu. Itu dosa. Lalu ... menggugurkan kandungan? Tidak! Tidak mungkin aku membunuh bayiku sendiri.
Tuminah memang gadis lugu. Polos hatinya. Ia tak tega menggugurkan kandungan yang berarti membunuh calon bayi. Ia takut. Takuuut sekali. Dan akhirnya ia putuskan: pulang.
Lihatlah, Tuminah menunduk tatkala hendak pamitan. Tas berisi beberapa lembar pakaian telah ia siapkan. Air matanya menetes. Sebenarnya ia sudah kerasan tinggal di rumah gede itu walau cuma jadi babu. Sesungguhnya Nyonya dan Tuan baik. Non Sarah dan Non Kiki pun sayang kepadanya. Tak pernah rewel. Nurut. Dan, mereka pun akrab dengan Tuminah. Tak pernah ia dimarahi. Tak pernah dibentak. Itu semua karena Tuminah anak yang baik. Pekerjaannya senantiasa beres. Perilakunya sopan, tutur katanya lembut, dan ia memang manis. Tapi, gairah Tuan yang membara itu tatkala menindihi tubuhnya di ranjang mewah di kasur empuk itu begitu menakutkan. Apalagi buah yang dihasilkan dari "pergaulan" terlarang itu, sungguh sebuah aib.
"Nyonya, maafkan saya," ucap Tuminah tersendat-sendat. "Saya mesti pulang."
"Lo, kenapa, Tum? Kamu tak betah tinggal di sini?" Sang Nyonya heran.
"Bukan karena itu, Nyonya." Tuminah agak tergagap.
"Lantas kenapa? Kami semua sayang kepadamu. Anak-anak juga begitu. Mereka akan kehilangan kamu, Tum. Apakah kami sering memarahimu? Atau gajimu terlalu kecil?" Nyonya membelai rambut Tuminah.
Tuminah menggeleng.
"Lalu kenapa?" Nyonya masih tampak heran.
Nyonya tak pernah mengerti. Bahkan tak memperhatikan perut Tuminah yang berisi janin hasil pergaulannya dengan Tuan, suaminya.
"Saya kangen nenek. Rindu kampung," dusta Tuminah sambil menunduk.
"Baiklah kalau begitu. Kami tak bisa memaksamu untuk tetap tinggal di sini. Tapi kalau kamu hendak kembali kemari suatu saat, pasti kami menerimamu dengan senang hati." Akhirnya Nyonya terpaksa merelakan.
Tuminah, Tuminah, perempuan desa yang lugu. Ke kota cuma jadi babu. Lantas dihamili majikan. Kini pulang kampung dengan membawa oleh-oleh: aib. Tapi itu lebih baik ketimbang membunuh bayi yang sudah empat bulan.
Marjono? Entahlah. Tuminah sudah sumpek. Bunuh diri? Tidak. Katanya bunuh diri itu dosa besar. Akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Lalu? Biarlah dan entahlah.
Tuminah yang malang. Nenek tak bakal bisa menerima anak jadah. Orang sedesa pun geger. Semua orang mencemooh anak yatim piatu itu. Dan, Marjono, kekasih tercinta itu....
"Tak kusangka, Tum. Aib menimpamu. Sungguh kejam," begitu komentar Marjono.
"Lantas bagaimana, Kang. Aku pasrah," ucap Tuminah sambil sesenggukan di pangkuan pemuda berkulit cokelat itu.
"Maafkan aku, Tum. Aku tak bisa menerimamu kembali," cetus Marjono terbata.
Bayi itu lahir juga pada akhirnya. Cakep dan montok. Tapi nenek tak bisa menerimanya. Bayi tak berdosa itu, kenapa dikatakan anak jadah, anak haram? Semua orang pun tetap tak bisa menerima kehadiran bayi itu. Katanya akan bikin sial. Tapi, Tuminah tak akan membuangnya di tempat sampah. Tak akan!
Tuminah sungguh polos hatinya. Perempuan desa ke kota jadi babu, pulang ke kampung membawa aib, kini kembali ke kota membawa bayi. Oleh-oleh buat sang Nyonya. Dan ia sendiri punya rencana lain. Ia telah memutuskan rencana itu.
Lihat! Tuminah berdiri di depan rumah gedongan di kawasan perumahan elite di Jakarta Selatan. Tangan kiri menjinjing tas. Tangan kanan memeluk bayi dalam seledang usang. Rumah itu tampak angkuh. Sepi. Ia menunggu pintu pagar terbuka. Ia menunggu sampai ada penghuni rumah itu melihatnya.
Benar. Nyonya tampak keluar pintu. Jantung Tuminah berdegup kencang. Adakah ia mau menerimaku kembali? Nyonya tampak ragu. Lalu ia mendekat. Menyaksikan dari dekat perempuan malang itu.
"Oh, Tuminah, akhirnya kamu kembali. Apa kataku. Anak-anak sering menanyakanmu, lo. Ayoh, masuk," ucap Nyonya senang sambil membuka pintu pagar.
Tuminah hanya mengangguk. Tetap berdiri mematung.
Nyonya tiba-tiba mengerutkan dahinya. Matanya tajam memandang wajah bayi dalam gendongan Tuminah.
"Tum, bayi siapa itu? Anakmu?" Nyonya tertegun.
Tuminah mengangguk.
"Cakep anakmu, Tum," puji Nyonya sambil mengelus kepala si bayi. Lalu menggendongnya. Tapi....
"Nyonya, maafkan saya, saya kemari hanya untuk menitipkan bayi ini," cetus Tuminah.
"Menitipkan....," Nyonya masih dilanda rasa heran.
Sekali lagi Tuminah mengangguk. "Saya nekat, Nyonya. Nekat jadi te-ka-we saja. Di Arab Saudi. Diajak Juminten dan Asih."
"Lo, maksudmu apa, Tum? Ini bayimu kamu titipkan di sini. Lantas kamu mau jadi TKW. La, bapaknya mana?"
"Ini anak Tuan. Saya... dulu diperkosa. Saya tak bisa menolak. Maafkan saya...."
Tuminah gadis desa. Ke kota jadi babu, pulang ke kampung bawa aib, kembali ke kota cuma menitipkan bayi, lantas kini mau jadi TKW. Tuminah memang lugu. Belum tahu dia. Di negeri ini atau di Arab Saudi atau di mana saja, "kecelakaan" itu akan terus terjadi, selama manusia tetap manusia, bukan malaikat. Tapi tekadnya sudah bulat, seraya berharap: semoga aib ini tidak terulang di Arab nanti. Nenek dan orang sedesa tak mau menerima anak jadah.
 Post
Post 








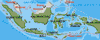














0 komentar:
Posting Komentar